Pengakuan Kalah Kader Polisi Bahasa kepada Tukang Parkir Bahasa - Refleksi dan Ulasan Buku “Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira” (2019)
Juni 07, 2022Bismillaahirrahmaanirrahiim~
Sebagai seorang kader polisi bahasa, saya selalu punya dorongan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa agar sesuai dengan KBBI dan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia – dulu EYD). Persoalan tata bahasa, penggunaan kata baku, huruf kapital, titik-koma, hingga yang paling klasik seperti penggunaan “di” yang disambung dan dipisah sering membuat diri ini gatel pengen ngelekke (ingin menegur).
Beberapa dari kalian yang membaca ini mungkin sudah pernah tertangkap basah membuat kesalahan berbahasa di medsos dan saya DM langsung, tetapi sebenarnya tidak semua hasrat untuk mengoreksi langsung tersalurkan. Beberapa tahun terakhir ini saya tersadar bahwa diri ini tak lebih dari sekadar rakyat jelata (T^T) alias masih kurang ilmu dan banyak salah. Akhirnya, saya lebih banyak diam. Parahnya, saya sendiri malah jadi ikutan takut menulis untuk diri sendiri. Gaswat.
Dengan niat mengembalikan kepercayaan diri dan menaikkan kasta, saya pun berikhtiar untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan teoritis saya terkait ejaan dan tata bahasa. Salah satunya lewat buku yang akan kita ulas ini, “Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira” karangan Iqbal Aji Daryono.
Yang saya tidak tahu adalah keputusan untuk menjawab masalah saya dengan buku ini merupakan sebuah kesalahan sejak dalam niatan.
Mas Iqbal (si penulis yang belakangan baru saya ketahui adalah esais jenaka yang cukup kondang) dalam sebuah artikel di Mojok menjelaskan mengenai keberadaan polisi bahasa dan dua tukang rese bahasa lainnya: hansip bahasa dan tukang parkir bahasa. Jika polisi bahasa menegakkan bahasa agar sesuai “rezim” Badan Bahasa, hansip bahasa menjadi penengah antara standar bahasa aparat dengan bahasa masyarakat, sedangkan tukang parkir bahasa berada di ujung lain dari keberpihakan ini. Mas Iqbal sendiri menggolongkan dirinya di kategori terakhir.
Waduh. Kader polisi bahasa kok ketemu sama tukang parkir bahasa? Yo berantem to yo, Say.
Eh, eh, saya gak berantem jambak-jambakan sama Mas Iqbal atau malah tweet war lho ya. Yang berantem adalah pikiran saya dengan buku beliau ini.
Niat hati belajar teori tata bahasa dan ejaan, dapatnya malah studi kasus permasalahan berbahasa sehari-hari. Topiknya pun disusun secara acak tanpa kategorisasi. Padahal, struktur yang lebih rapi tampaknya bisa membantu saya memahami poin-poin gagasan Mas Iqbal yang amat beragam dengan lebih baik. Buku ini juga masih mengandung kesalahan-kesalahan ketik dan ejaan lantaran memang tidak disunting oleh editor. “Supaya tidak mengurangi keaslian gaya penulisan penulisnya”, begitu kata Mas Iqbal.
Pokoknya ia jelas-jelas bukan buku yang saya cari, lah.
Ya, sebenarnya buku ini tidak 100% mengecewakan, sih. Malah banyak juga hal baru yang saya pelajari. Akan tetapi, saya tetap tidak bisa tidak merasa mangkel dan bingung dengan ketidakseriusan yang terpancar darinya. Bahkan, saya sempat berpendapat bahwa saya tidak paham apa signifikansi keberadaan buku ini bila dibandingkan dengan buku-buku yang setema (sok-sokan banget, padahal baca buku kebahasaan yang lain saja belum pernah).
Yang lebih membuat mangkel adalah saya kemudian sadar bahwa sebenarnya kemangkelan ini bisa dihindari andaikan saya mau repot-repot membaca sinopsis yang ditulis dengan cukup gamblang di sampul belakang buku ini sebelum terburu-buru membawanya ke meja kasir Togamas, atau setidaknya sebelum saya membuka halaman pertamanya. Harga diri saya sebagai kader polisi bahasa jatuh lantaran malu, malu atas rasa kesal yang sebenarnya saya buat-buat sendiri (T^T).
Apalagi setelah itu saya baru ngeh bahwa tidak seperti memilih calon suami, buku ini memang tidak boleh diseriusin. Mas Iqbal sendiri berharap bukunya tidak disejajarkan dengan buku-buku bahasa serius macam kamus dan kawan-kawannya di toko buku. Bahkan Pak Edi, pemilik Diva Press yang menerbitkan buku ini berkata dengan mulutnya sendiri, “Buku ini tu gak penting!”
Asem.
Di titik ini saya cuma bisa cengengesan gak jelas. Mencari keseriusan dalam buku yang sejak awal dibuat untuk tidak diseriusin ini seperti mencoba membeli semen di toko roti, yo ra mungkin ketemu!
Nah, seperti halnya tukang parkir yang tidak keliatan saat kita masuk toko dan baru nongol saat kita mau cabut, ketika saya mulai bisa menerima “kekalahan” tersebut, saya pun juga mulai melihat dengan lebih jernih hal-hal penting dalam buku ini yang tadinya terbayangi oleh kekesalan saya.
Hakikat bahasa adalah kesepakatan komunikasi dalam sebuah komunitas yang terbatas oleh wilayah dan waktu tertentu. Menurut Mas Iqbal, selama suatu kata atau ungkapan dipahami maknanya oleh kedua belah pihak yang berkomunikasi, maka ia dianggap benar. Hal ini berbeda dengan persoalan baku dan tidak baku. Oleh karena itu, slogan Badan Bahasa yang berbunyi “Berbahasa Indonesialah dengan baik dan benar” menjadi kurang tepat ketika ia hanya difokuskan pada ejaan dan kebakuan bahasa.
Namun, sebelum beranjak ke persoalan kaidah, Mas Iqbal menyarankan pembaca untuk lebih memperhatikan logika dalam berbahasa. Saran ini didasarkan pada banyaknya kegagalan nalar berbahasa yang beliau temukan di sekelilingnya. Sebagai contoh, dalam model kalimat yang sering kita dengar, “Guru mengajarkan kita sopan santun,” kita bisa dengan yakin menjawab “guru” ketika ditanya siapa yang mengajar. Namun, ketika ditanya “siapa yang diajari?” dan “apa yang diajarkan?”, kita mulai melihat kerancuan dalam kalimat tersebut.
Contoh di atas dan banyak contoh logika berbahasa lain yang dipaparkan Mas Iqbal dalam buku ini diam-diam berhasil membuat saya lebih aware terhadap hal tersebut, terbukti dari banyaknya kerancuan makna yang saya temukan ketika sedang menyunting naskah yang saya tulis sebelum membaca buku ini.
Haduuuh, begini ini, sok-sokan ingin jadi polisi bahasa? Well, menurut Mas Iqbal, kekurangan seperti ini memang biasa ditemukan pada kalangan polisi bahasa lantaran mereka lebih fokus pada kebakuan kata dan ketepatan ejaan, sementara keterampilan menempatkan kata dalam konteks kalimat tidak cukup terasah.
Buku ini juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam berbahasa. Kembali kepada hakikat bahasa berupa kesepakatan komunikasi, berbahasa sesuai konteks situasi menjadi sangat penting. Seseorang perlu memperhatikan di mana ia berada dan siapa yang berada di sekelilingnya agar mampu menjalin komunikasi dalam level yang setara. Pemilihan topik atau penggunaan kata yang tidak dipahami audiens justru akan menimbulkan kegagalan komunikasi di antara keduanya.
Poin ini menjadi pengingat bagi saya yang sejak pulang dari program pertukaran pelajar jadi lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Dalam perspektif saya, ada hal-hal yang lebih mudah dijelaskan menggunakan Bahasa Inggris. Lidah ini juga sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut selama hampir setahun lamanya. Fenomena komunikasi ala anak Jaksel ini pun muncul secara natural tanpa ada niatan menyombongkan diri atau yang lainnya. Ketika saya mulai sering berkomunikasi secara tekstual lewat Instastory, saya tersadar bahwa meskipun saya mendapat banyak teman asing baru, saya mengesampingkan fakta bahwa viewers saya lebih banyak yang berbahasa Indonesia daripada yang berbahasa Inggris. Konten yang sebenarnya bisa dinikmati banyak orang akhirnya hanya jadi angin lalu lantaran audiens sudah lebih dulu merasa berjarak dengannya.
Poin terakhir yang tidak kalah penting dari buku ini adalah berbahasa Indonesia dengan gembira. Maksudnya, dalam perannya sebagai media komunikasi, bahasa juga merupakan media untuk mengekspresikan rasa. Mas Iqbal ingin mengajak pembacanya untuk menikmati keindahan berbahasa dengan majas, gurauan, dan ekspresi-ekspresi lain yang membuatnya lebih menyenangkan. Hal tersebut beliau contohkan langsung lewat tulisan-tulisannya di buku ini yang sukses membuat saya cengengesan sendiri. Saya lupa bahwa tulisan tidak hanya memberikan informasi yang bermanfaat, tetapi juga bisa membuat orang lain bahagia.
Saya tidak menyangka sih, bakal butuh waktu lima bulan sejak selesai membaca buku ini untuk akhirnya mampu mengakui kekurangan diri, berdamai dengan hal itu, dan mulai menerima pelajaran-pelajaran penting di dalamnya.
Membaca buku ini seperti merasa kesal ketika harus membayar tukang parkir yang tadinya tidak kelihatan, tetapi ternyata beliau telah menyelamatkan kunci motor yang masih menggantung di stop kontak. Kalau saya tidak bertemu buku ini sebelum saya belajar lebih lanjut mengenai kaidah berbahasa yang baku, mungkin saya akan kehilangan esensi-esensi penting dalam berkomunikasi dan akhirnya menjadi polisi bahasa yang sombong dan egois.
Tiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Ada hal-hal yang hanya diketahui seorang polisi bahasa, tetapi ada juga hal-hal yang hanya diketahui seorang tukang parkir bahasa, begitu pun hansip bahasa. Perbedaan perspektif dan peran ada bukan untuk saling adu atau saling merendahkan, melainkan untuk saling melengkapi.
uWuuuuuu, berpelukaaaaan~


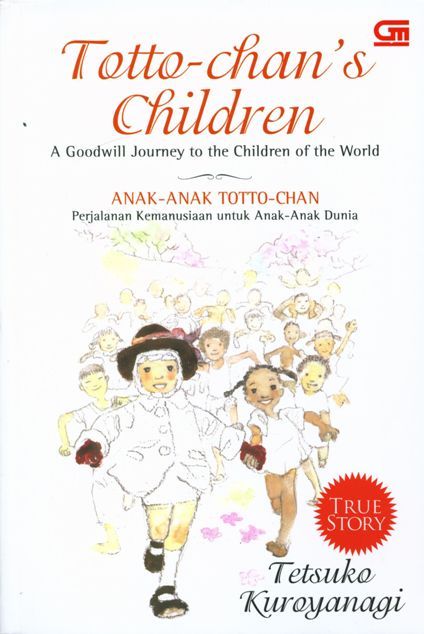











0 comment