Belenggu Lemburku
Juni 27, 202201:16 dini hari.
Saya masih duduk di depan komputer kantor. Di dekatku ada Riyan yang sedang melakukan sesuatu di iPadnya. Di seberang ruangan ada Billy dan Mel yang curhat satu sama lain tentang orang tua, pola asuh, dan inner child. Sementara, Putra masih berkutat dengan pekerjaannya di lantai atas.
Pemandangan seperti ini tidaklah asing. Hampir semua orang di kantor ini pulang melebihi jam kerja resmi. Setidaknya 30% orang baru mematikan komputer selepas tengah malam. Beberapa orang yang tinggal di mes kantor kadang tinggal lebih lama di ruang kerja untuk ngobrol atau mengerjakan proyek pribadi, seperti kami malam ini.
Fenomena kerja lembur di kantor kami mengingatkan saya pada sebuah materi sosiologi yang saya pelajari di saat pertukaran pelajar di Jepang tentang budaya bekerja di sana. Di Jepang, rata-rata pekerja kantoran pulang naik kereta atau bus terakhir hari itu, sampai di rumah, menyiapkan diri dan bekal makanan untuk esok, tidur, bangun pagi, lalu berangkat lagi ke kantor, dan siklus terulang lagi. Faktor utama yang sering disebutkan saat membahas ini adalah konsep life-time employment yang umum diterapkan di Jepang. Seorang pegawai akan dipertahankan hingga ia masuk usia pensiun sehingga ia diharapkan untuk setia terhadap perusahaan tersebut. Faktor lain adalah budaya conformity atau mengutamakan kepentingan bersama dibanding individu sehingga ada perasaan bersalah apabila pegawai pulang lebih dahulu, apalagi lebih awal daripada atasan mereka.
Saat belajar tentang ini, saya keheranan sendiri, apalagi ini fenomena yang sangat umum terjadi di negara ini. Melihat pria berjas membawa tas kerja melintasi jalanan kota di dini hari menjadi hal yang biasa. Saya sendiri melihat ayah host family saat di Jepang pulang pukul 10 malam saat anak-anaknya yang masih kecil sudah tidur dan berangkat lagi pukul 6 pagi ketika anak-anaknya belum bangun. Hampir tak ada waktu untuk keluarga kecuali di akhir pekan. Saya pun ragu apakah ia punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Tak heran, banyak ditemukan kasus bunuh diri di Jepang karena kerja berlebihan.
Saat itu, saya berjanji ke diri saya sendiri untuk tidak menjadi seperti itu. Saya juga optimis dengan kultur kerja di Indonesia yang cenderung lebih santai. Namun, waktu itu saya lupa mempertimbangkan bagaimana saya sebagai individu bekerja. Sejak kecil, saya selalu punya masalah dengan manajemen waktu. Saya sering mepet atau terlambat datang ke sekolah. Hal serupa terjadi saat kuliah dan menjadi semakin parah, terutama dalam hal pengumpulan tugas. Saat di Jepang pun, saya sering terlambat masuk kelas, padahal jarak ke kampus hanya 10 menit dari asrama. Dengan kata lain, saya memang suka menyepelekan waktu. Saya juga perfeksionis, punya standar tinggi, terutama soal apa yang saya hasilkan. Dikaitkan dengan waktu tadi, semakin besar tugasnya, semakin saya beranggapan bahwa saya butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Sementara, saya tidak cukup memperhatikan berapa waktu yang sebenarnya saya miliki dan juga langkah apa saja yang perlu saya tempuh untuk menyelesaikan suatu tugas. Karena terlalu santai di awal, alhasil semua pekerjaan terkumpul di akhir dan saya pun biasa lembur pada hari-hari pengumpulan.
Ketika mulai kerja di Tangerang, saya sempat bisa mengontrol waktu kerja saya saat masih tinggal di kos. Namun, sejak pindah dari kos ke mes kantor, kebiasaan lembur saya kambuh lagi dan sulit disembuhkan. Barangkali karena lokasi mes yang berada di bangunan kantor itu sendiri, batas antara ruang kerja dengan ruang istirahat menjadi kabur. Kalau dulu saya mengusahakan pulang awal untuk menghindari mobilisasi di malam hari, sekarang saya tidak perlu mengkhawatirkan itu dan bisa berangkat dan pulang kapan saja. Lagi-lagi saya menyepelekan hal tersebut dan saya pun baru bisa semangat bekerja di malam hari karena sudah makin dekat dengan deadline. Hal yang mirip terjadi juga pada teman-teman lain yang pindah ke mes. Beberapa bahkan ada yang sengaja pindah ke mes supaya tidak perlu khawatir soal pulang larut malam tiap kali butuh begadang.
Awalnya saya berpikir, apakah kami sering lembur karena kami bekerja di daerah ibukota yang fasenya cepat? Namun, pertanyaan itu terpatahkan ketika saya membandingkan dengan kantor-kantor arsitektur lain yang di Jakarta yang masih bisa pulang teng-go. Usut punya usut dengan anak-anak studio kami, katanya kantor terbiasa mengambil proyek terlalu banyak. Setiap hari selalu ada yang harus dikerjakan, entah karena kebutuhan pekerjaaan pembangunan di lapangan atau karena dikejar-kejar klien satu ke klien lainnya. Tidak ada ruang untuk bersantai. Apalagi kantor studio juga perlu mengejar setoran bulanan untuk menghidupi seluruh karyawan. Nah, soal setoran bulanan ini mungkin tidak berlaku di divisi penerbitan tempat saya bekerja karena ia bergerak lebih seperti CSR. Namun, dari segi proyek yang dikerjakan tidak jauh berbeda. Jumlah karyawan sedikit, sedangkan banyak hal yang harus dilakukan untuk memajukan literasi arsitektur di Indonesia.
Namun, tidak semua faktor datang dari stimulus eksternal. Ada juga anak-anak yang sengaja memilih untuk lembur. Ada rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang tinggi, juga kepada klien dan para tukang yang menanti gambar-gambar kami sebagai acuan pembangunan di lapangan. Kemudian, motivasi itu didukung dengan fasilitas mes di kantor yang memungkinkan kerja lembur. Beberapa lagi ada yang suka dengan kebersamaan yang tercipta di kantor saat lembur sehingga kerja lembur tidak terasa buruk-buruk amat. Jadi, mumpung ada temannya, sekalian saja. Di sisi lain, beberapa anak tinggal di kantor lebih lama meski sudah “selesai” dengan pekerjaan mereka untuk mengerjakan proyek pribadi atau hobi yang membantu mereka menyeimbangkan kebutuhan personal dengan tuntutan kerja di kantor. Salah satunya juga karena tidak yakin bisa mengerjakan itu kalau sudah kembali ke kamar dan menyentuh kasur.
Meski begitu, hal tersebut tidak membenarkan kebiasaan lembur itu sendiri. Setidaknya bagi saya, sekalipun itu sudah menjadi kebiasaan. Karena lembur, saya jadi sering kecapekan dan tertidur di jam kerja. Saya juga jarang olahraga karena sering bangun kesiangan. Alasan yang sama membuat saya malas main keluar di hari libur, apalagi badan merengek minta jatah tidurnya yang selama ini tertunda. Jam makan dan tidur saya juga tidak teratur. Pokoknya berantakan. Yang paling parah adalah tidak adanya waktu untuk melakukan refleksi seperti menulis pemikiran atau sekadar mengisi jurnal agenda harian. Hari-hari rasanya berlalu begitu saja. Saya juga tidak sempat ikut kajian untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Boro-boro, shalat subuh saja sering terlewat karena bangun kesiangan. Menyedihkan. Oh, jangan tanya kondisi kamar saya. Jelas berantakan.
Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih diberi kesehatan dan jarang sakit. Namun, saya selalu ingat kata-kata Bapak, “Nduk, mungkin sekarang sekarang gak kerasa, tapi nanti kalau kamu sudah tua baru terasa dampaknya.” Tidak terbayang bagaimana nanti kalau saya justru jatuh sakit ketika sudah saatnya merawat anak dan mungkin juga merawat orang tua. Saya juga tidak ingin berakhir seperti keluarga-keluarga Jepang yang tidak punya banyak waktu untuk bersama dalam kesehariannya. Namun, rasanya sulit merubah kebiasaan ini: kerja lembur, kesiangan, masuk telat, tambal jam kerja, lembur lagi, kesiangan lagi. Begitu terus, menjadi siklus yang sulit dipecahkan.
Apakah saya pernah dalam kondisi ideal? Alhamdulillah pernah. Masa pengerjaan tugas akhir justru jadi momen saya hidup paling sehat. Karena semua progres harus dikerjakan dalam studio kampus yang dibatasi waktunya dari pukul 8 sampai pukul 4 sore saja, saya pun jadi benar-benar fokus memanfaatkan waktu itu untuk bekerja. Di luar itu saya bisa kajian, mempelajari hal baru, bersih-bersih kamar setiap hari, bahkan masih sempat nonton drama Korea untuk melepas stress. Saya juga sempat berhasil melakukan itu saat tinggal di Jepang, walaupun kemudian jadi kacau ketika waktu shalat mulai berubah akibat pergerakan matahari. Saat masih dalam masa job-seeking di awal pandemi, saya juga sempat hidup teratur dan bisa membagi antara pekerjaan freelance, pekerjaan rumah, dan entertainment. Namun, di semua kondisi itu memang beban kerjanya lebih ringan dan saya tidak harus memperjuangkan pendapatan finansial tertentu.
Perlu diakui, memang ada pergeseran prioritas dalam hidup saya. Somehow, saya juga tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk keluar dari belenggu lembur ini. Namun, saya bingung bagaimana memulainya, dan sekalinya dicoba, saya malah jatuh ke lubang yang sama lagi ...
Barangkali memang ada yang harus saya korbankan. Namun, apakah saya siap untuk melepaskannya?
Jam komputer menunjukkan pukul 04:56. Saya pun bergegas mengambil air wudhu dan shalat subuh di ruang sofa kantor. Mata yang berat menggoda saya untuk rebahan di atas sajadah dan saya pun tertidur masih dalam balutan mukena, menanti dibangunkan oleh suara para pegawai yang satu per satu masuk ke kantor.


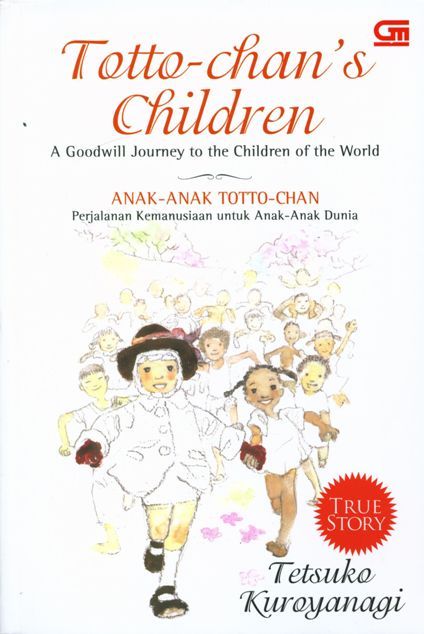









0 comment