Mencicipi Rasa Online Shaming: Socialphobia (2015) & Listen to Love (2016)
November 25, 2018
The so-called internet, sistem komputer yang pertama kali dibuat tahun 1969 ini kini berkembang dengan semakin pesat. Berbagai macam inovasi di dalamnya terus diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan seakan mempersempit jarak antarindividu di seluruh penjuru dunia. Berkat internet, “dunia” manusia mengalami ekstensi mewujudkan ruang lain yang kita sebut “dunia maya” dan di dalamnya banyak fenomena baru terjadi. Salah satunya online shaming.
Online shaming adalah bentuk “pengadilan” internet di mana targetnya dipermalukan secara publik menggunakan teknologi seperti media sosial. Peserta shaming melihat ini sebagai kesempatan untuk “meluruskan” para pengguna internet yang dianggap melakukan sesuatu atau merilis pernyataan yang bertentangan dengan nilai yang ada dalam komunitas yang bersangkutan. Dilihat dari definisinya, fenomena ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang ada baiknya pula bila dijalankan dengan penuh pertimbangan. But, what happen when it goes too far?
Beberapa kasus penting terkait online shaming tercatat ada sejak tahun 2000-an, masa di mana media sosial mulai booming. Meminjam istilah Jon Ronson, it was the time when the voiceless was finally given a voice. Setiap orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Dampak online shaming terhadap korbannya sangatlah signifikan karena pengaruhnya tidak berhenti di dunia maya saja, tapi juga di dunia nyata, misal dikucilkan oleh lingkungan sekitar atau diberhentikan dari pekerjaan.
Walau sudah beberapa kali mendengar dan mendapat gambaran tentangnya, fenomena online shaming belum pernah terasa sangat nyata hingga akhirnya saya menyaksikannya terjadi di komunitas saya sendiri. Semua berkat mencuatnya sebuah kasus pelecehan seksual yang membawa nama almamater saya di awal bulan November ini. Somehow I knew when it was coming, dan saya terus-terus merasa khawatir terhadapnya. Niatan baik netizen untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kasus ini perlahan berubah menjadi amarah yang tidak terkontrol, dan saya tidak tahan melihat lingkungan saya tanpa sadar secara berjamaah sedang menghancurkan kelangsungan hidup seseorang.
WHAT’S THE TASTE OF ONLINE SHAMING?
Mengamini pendapat Garin Nugroho, film dan produk sinematografi lainnya adalah bentuk cerminan dari budaya, meski kuat lemah kadarnya suka-suka si kreatornya. Korea Selatan adalah salah satu negara yang produk sinematografinya cukup berani mengupas dan mengkritik fenomena masyarakatnya. Online shaming adalah salah satu isu yang tidak ketinggalan untuk diangkat. Terdapat dua judul (sejauh yang pernah saya tonton) yang menurut saya sangat relevan dengan isu ini, yakni film Socialphobia (2015) dan drama Listen to Love (jTBC, 2016).
[SOCIALPHOBIA]
[Original Title] 소셜포비아 (Socialphobia)
[Director] Hong Seok-Jae
[Writer] Hong Seok-Jae
[Genre] Drama-thriller
[Release Date] March 12, 2015
Tokoh protagonis dalam film ini adalah Ji-Woong dan Young-Min, dua orang pemuda yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota polisi. Bersama tujuh warga biasa yang baru mereka kenal, keduanya turut serta dalam aksi penyergapan apartemen seorang netizen berID Re-Na yang membuat gempar jagad maya negeri gingseng setelah merilis tweet kontroversial tentang meninggalnya seorang tentara. Berlagak seperti “delegasi” dari seluruh masyarakat Korea, mereka merekam dan menyiarkan secara langsung aksi mereka, berharap pada akhirnya mendapat permintaan maaf dari Re-Na. Siapa sangka, alih-alih mendapat permintaan maaf, mereka justru menemukan jasad Re-Na menggantung di balkon apartemennya. Walau telah dinyatakan sebagai kasus bunuh diri oleh pihak kepolisian, mereka mencurigai adanya permainan di balik ini semua. Mereka kemudian mencoba menguak misteri tentang siapa yang sesungguhnya telah membunuh Re-Na. Film ini mengeksplorasi fenomena kecanduan internet, cyber bullying, fobia sosial, dan kurangnya moral serta harga diri di kalangan anak muda Korea masa kini.
(English subtitle is available)
[Original Title] 이번 주, 아내가 바람을 핍니다 (My Wife's Having an Affair this Week)
[Director] Kim Suk-Yoon
[Genre] Romance, melodrama, comedy, family
[Release Date] October 28 - December 3, 2016
[Network] jTBC
[Episodes] 12
Diadaptasi dari serial drama Jepang produksi Fuji TV tahun 2007 (era mulai munculnya fenomena online shaming!), Listen to Love bercerita tentang Do Hyun-Woo, seorang pria setengah baya dengan pengalaman 10 tahun berkarir sebagai produser variety show di sebuah stasiun televisi ternama di Korea. Tanpa sengaja ia mengetahui bahwa istrinya, Jung Soo-Yeon, telah berselingkuh dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Mencoba untuk mempertahankan pernikahannya, Do Hyun-Woo meminta saran dari para anonim di sebuah jaringan sosial online dengan menggunakan nama ID Toycrane. Seiring dengan progres cerita, para anonim yang ia mintai saran mulai bertindak kelewat batas dan justru berbalik menyerang dirinya dan keluarganya.
(Indonesian subtitle is available)
Pengalaman menonton kedua produksi ini memberikan alaram ketika saya akhirnya menyaksikan fenomena online shaming terjadi di lingkungan saya, dan saya tercengang dengan keakuratan dan detail yang ditampilkan dalam film dan drama tersebut. Keduanya meliputi banyak hal mengenai perilaku manusia terkait dunia maya, antara lain:
1. THE NEED FOR ACCEPTANCE AND APPROVAL
Manusia secara naluriah senantiasa mencari penerimaan dari orang lain, to be viewed as a good person, to be someone that you can trust. Salah satu caranya adalah dengan turut serta menegakkan nilai yang ada dalam komunitas tempat suatu individu berada, atau sederhananya berkumpul dengan orang-orang yang satu pikiran dengan kita. Jon Ronson said, “We surround ourselves with people who feel the same way we do, and we approve each other”. Twitter dalam Socialphobia adalah contoh mutlak dari apa yang disebut Jon Ronson sebagai mutual approval machine. Ji-Woong, Young-Min, dan sekumpulan pemuda random di film tersebut kemudian membawa hubungan mutual approval mereka dari dunia maya ke dunia nyata dan secara berjamaah bertindak sebagai pahlawan dengan menyergap apartemen Re-Na.
Dalam Listen to Love, beberapa netizen anonim yang bergabung dalam jejaring online tempat Do Hyun-Woo mencurahkan keluh kesahnya digambarkan sebagai orang-orang yang di kehidupan nyata tidak memiliki posisi yang cukup signifikan di antara masyarakat, seperti kuli bangunan, pengangguran, remaja yang kecanduan game, dan juga seorang antisosial yang selalu bergumul di bawah selimut di dalam kamarnya yang gelap. Gagal mendapat penerimaan di dunia nyata, mereka pun mencari penerimaan di dunia maya (sounds like me a few years ago). Meminjam istilah Remotivi, menjadi “pahlawan keyboard”, menurut Dr Aitchison, seorang peneliti dari Irish Research Council Fellow di University College Dublin, “is a relatively low cost way to feel like you are doing something noble,”
2. JUSTIFIKASI BERDASARKAN INFORMASI DAN MEDIA YANG TERBATAS
Menurut Lucy Doyle dalam tulisannya di situs parentinfo.org, menjadi bagian dalam kelompok yang besar dan anonimitas yang lazim di dunia maya dapat mendorong munculnya mentalitas massa, di mana seseorang mampu mengatakan hal-hal yang tidak mungkin mereka katakan di hadapan seseorang di dunia nyata. Internet juga memberikan tingkatan jarak: ketika kamu tidak bisa melihat orang yang kamu serang, atau efek yang ditimbulkan dari kata-katamu terhadapnya, lebih mudah bagimu untuk kehilangan rasa empati.
Segala informasi yang kita terima sangatlah terbatas, seterbatas Instastory yang hanya mewakili sekian detik dari keseluruhan hidup seseorang. Setiap orang punya pola pikir dan pemahaman yang berbeda-beda. Namun, seringkali kita mereduksi seseorang menjadi sebuah status, sebuah tweet, atau sebuah komentar yang ia tulis sambil lalu ketika menunggu antrian ATM. Dalam Listen to Love, netizen-netizen anonim yang menuntut Do Hyun-Woo untuk menceraikan istrinya mereduksi sosok Jung Soo-Yeon menjadi seorang peselingkuh saja. Tidak ada yang tahu bagaimana perannya sebagai istri, ibu, sekaligus manajer di perusahaannya; tidak ada yang tahu apa yang dialami dan yang dirasakannya sehingga ia terdorong untuk berselingkuh; dan tidak ada yang tahu bagaimana sikap Do Hyun-Woo sesungguhnya turut berkontribusi dalam munculnya perselingkuhan ini. Ji-Woong dan Young-Min dalam Socialphobia, yang awalnya turut geram dengan sikap Re-Na di media sosial perlahan justru menjadi iba seiring terkuaknya sosok Min Ha-Young, wanita di balik akun kontroversial tersebut.
3. VIGILANTISME: YANG PUNYA MASALAH SIAPA, YANG MARAH SIAPA
Vigilantisme secara sederhana dapat diartikan sebagai “main hakim sendiri”. Ini adalah situasi di mana orang-orang mengambil peran penegak hukum tanpa diberikan kewenangan legal, tanpa mempertimbangkan apakah aksinya benar-benar berbasis keadilan atau tidak (Tirto.id, 2017).
Saya turut merasakan frustrasi yang dialami Do Hyun-Woo ketika akhirnya ia memutuskan untuk secara tulus berdamai dan memaafkan Jung Soo-Yeon, tetapi netizen-netizen anonim ini bersikeras sebaliknya. Sebagian bahkan meneror dan mengancam untuk membongkar identitas istrinya tersebut. Saya juga berjengit ketika pemuda-pemuda random dalam Socialphobia akhirnya memutuskan menyergap apartemen seorang netizen anonim. “Apa-apaan sih manusia-manusia ini?” pikir saya. Namun, dalam situasi kontroversial yang mengundang amarah publik, mengata-ngatai seorang peselingkuh, plagiator, pemerkosa, atau orang rasis terasa benar untuk dilakukan, bukan?
Then, what might happen to the victim of online shaming?
Jon Ronson dalam sebuah presentasi TED menceritakan kisah Justine Sacco, seorang pegawai PR asal New York yang mengalami online shaming setelah tweet leluconnya disalahartikan sebagai pernyataan rasis. Hati saya mencelos mendengar pilihan kata Ronson yang ironis tetapi sangat jujur, “Thousands of people around the world decided that it was their duty to get her fired… Justin was fired of course, because social media demanded it.”
Dalam Socialphobia, setelah salah seorang korban online shaming dibongkar identitasnya (nama asli, foto, alamat rumah, pendidikan, name it all), ia harus putus sekolah dan bahkan memutuskan untuk mengganti namanya. Well, how could you have a normal life when your name has been known as the identity of a public enemy? Terus terang saya juga turut merasa takut ketika Jung Soo-Yeon dalam Listen to Love mulai mendapat terror di tempat kerjanya. Dia merasa seperti terus diawasi dan oh, apa yang akan terjadi pada Joon-Soo, anak mereka yang baru berusia enam tahun bila identitas Jung Soo-Yeon terbongkar? Tumbuh dewasa dengan label anak tukang selingkuh?
Kita memaki, mengata-ngatai, dan berpikir bahwa orang ini pasti sangat bebal hingga kata-kata halus tak mungkin mempan terhadapnya. Namun, sesungguhnya mereka sama-sama manusia seperti kita yang juga mencari penerimaan. But we left them with fear and often their apologies become unheard. Lantas dalam ketakutan itu, ketika tidak ada lagi yang mempercayaimu, tidak ada lagi yang membutuhkan keberadaanmu, committing suicide sounds like a great option, isn’t it? Well, bagaimana tidak ketika kamu akhirnya gagal untuk mempercayai dirimu sendiri, thanks to thousands of people around the world who told you get out (Jon Ronson, 2015).
Setelah terus menerus diajak untuk turut percaya bahwa kematian Re-Na disebabkan oleh pembunuhan, Socialphobia membungkam penonton di penghujung film dengan mengungkap bahwa Re-Nalah yang memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Seperti Ji-Woong dan Young-Min, I didn’t find it easy to understand that “nice” people like us are capable to push someone to take his or her own life. Yet we do.
Malam itu, 9 November 2018, empat hari setelah kabar pelecehan seksual di kampus kami mencuat, saya dan beberapa sahabat saya memantau perkembangan respons publik di internet yang semakin ganas menyerang si pelaku pelecehan. Dalam grup WhatsApp kami yang kecil itu terlontar satu doa yang saling kami amini, “Semoga ia tidak bunuh diri.”
HOW TO NOT KILL A PERSON ONLINE
Menalar pendapat dari Remotivi tentang online shaming: iya, melecehkan orang lain secara seksual itu salah, tapi mempermalukan orang sampai depresi juga salah. Before things are going even more too far, mari kita mencoba untuk tidak jadi seorang pembunuh.
1. Kita perlu memahami bahwa internet adalah perpanjangan dari dunia nyata. Oleh karena itu, menurut Webroot.com, standard norma yang dipakai saat online juga sama dengan yang dipakai di dunia nyata. Bagi muslim, menurut ulama, tulisan itu hukumnya sama seperti lisan, sama-sama dicatat juga oleh malaikat. If you have nothing good to say, better just shut up. The internet is as public as our mosques, our school, and our shopping malls. You won’t yell at random people in malls, will you?
2. Everyone has their own condition. Kata dosen panutan saya, bangsa kita ini kultur mendengarkannya sangat minim, lebih dominan keinginannya untuk didengar. Padahal, kultur mendengarkan itu penting supaya kita tidak salah memahami situasi. Sebelum membuat komentar terhadap sebuah pernyataan atau sebelum kita membagikan berita, coba kita cari tahu terlebih dahulu kebenarannya, bagamaina motif dan latar belakang si pembuat pernyataan. Cek and recheck agar tidak berujung sebagai hoax dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Marilah kita coba untuk saling mengerti sehingga tidak semudah itu dehumanize orang lain.
Nah, kalau memang yang bersangkutan itu bermasalah dan secara pribadi cukup dekat dengan kita, lebih baik ditegur baik-baik secara personal dengan tatap muka atau direct massage dan beri kesempatan pada orang tersebut untuk menjelaskan situasinya serta meminta maaf. Tidak ada yang suka dipermalukan di depan umum. Orang yang mengalaminya mungkin akan mengelak dan mencari pembenaran atas statementnya, and we know the rest of the story.
3. Best advice ever: limit our use of social media. Sudah banyak sekali bahasan tentang bagaimana internet dan media sosial sedikit banyak memberikan pengaruh negatif pada kesehatan mental dan produktivitas manusia. Maka, untuk menghindari dampak tersebut dan fenomena problematis seperti halnya online shaming, alangkah baiknya kita membatasi saja penggunaan media sosial. Alihkan perhatian pada kegiatan lain yang memberikan stimulus positif pada diri kita.
4. Namun, kalau kamu menemukan seseorang sedang dipermalukan secara tidak adil, seperti saran Jon Ronson, the very best thing that we can do, “is to speak up, because I think the worst thing that happened to Justine was that nobody supported her -- like everyone was against her, and that is profoundly traumatizing,” meskipun tidak akan mudah.
Last advice: master these things you will also develop the skill to not get killed instead :) Good luck!
Last advice: master these things you will also develop the skill to not get killed instead :) Good luck!
EPILOG
Socialphobia dan Listen to Love telah memberi banyak pelajaran dalam memahami fenomena online shaming baik dari sisi korban maupun sisi pelaku. Mereka sukses mensimulasi sensasi dan kecemasan yang dirasakan ketika fenomena ini terjadi di hadapan kita. Socialphobia jelas menampar saya dengan lebih keras lewat ironinya. Namun, saya berharap kita punya ending yang lebih baik seperti Listen to Love. Do Hyun-Woo dan Jung Soo-Yeon belajar bahwa kesalahan tetaplah kesalahan dan tentunya tidak mudah dilupakan, tetapi manusia selalu punya pilihan untuk memaafkan. Baiknya lagi ak hanya tokoh-tokoh utama saja yang bisa mengambil pelajaran, netizen-netizen yang terlibat juga perlahan mulai berkaca dan melihat ke dalam diri mereka sendiri. Irina Raicu dalam tulisannya di situs berita ABC mengatakan, “In fact, sometimes the people who start an online shaming "wave" later regret their actions. Regret, in this case, seems to be a recognition of the fact that their own actions didn't match up with their values.”
To all shamees who become aware of their wrongdoing and regret it, you may not have the right to be forgotten, but you deserve to be heard and to be forgiven. Semoga jiwa dan ragamu dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik untuk masalahmu.
So, are we ready to forgive?
Fukuoka, 25 November 2018
________________________________________
________________________________________
Note:
1. Please help me improve my writing skill by rating this article between the ranges of 0 to 10 and give your opinion about things that I can improve in the comment section below. Thank you very much for your kindness :)
1. Please help me improve my writing skill by rating this article between the ranges of 0 to 10 and give your opinion about things that I can improve in the comment section below. Thank you very much for your kindness :)
2. All references and more about netizen ethic: Pinterest Board – [Blue Think] Online Shaming




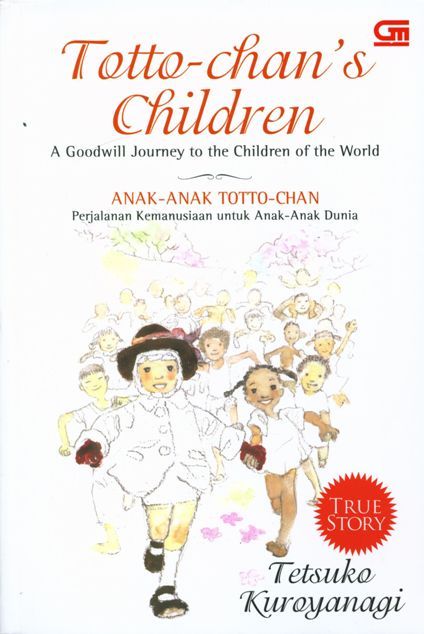









0 comment